(Resensi) A Blue New Deal: Why We Need a New Politics for the Ocean
Judul buku: A Blue New Deal: Why We Need a New Politics for the Ocean
Penulis: Chris Armstrong
Penerbit: Yale University Press (versi paperback terbit 23 Mei 2023 dan versi hardcover terbit 22 Februari 2022)
Resensi oleh: Elis Nurhayati
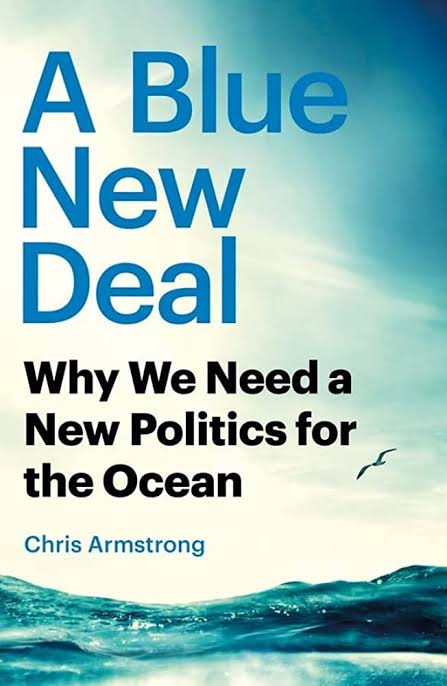 Pemerintah di berbagai negara kerap berbicara tentang pekerjaan ramah lingkungan (green jobs) dan revolusi industri yang memperhatikan kelestarian ekologi. Negara-negara anggota PBB pun berlomba menciptakan kesepakatan baru yang mengaplikasikan tiga prinsip keberlanjutan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial.
Pemerintah di berbagai negara kerap berbicara tentang pekerjaan ramah lingkungan (green jobs) dan revolusi industri yang memperhatikan kelestarian ekologi. Negara-negara anggota PBB pun berlomba menciptakan kesepakatan baru yang mengaplikasikan tiga prinsip keberlanjutan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial.
Tujuan dari semua upaya ini adalah untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang makin tak terkendali, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ketidaksetaraan dalam sistem politik dan ekonomi kita.
Tapi di manakah warna biru dari semua ini? Seperti yang ditulis di buku Chris Armstrong terbitan pertama tahun 2022 ini, “tidak akan ada transformasi hijau tanpa transformasi biru yang berjalan secara bersamaan”.
Bagi sebagian besar dari kita yang hidup di daratan, ekosistem laut tidak langsung terlihat secara kasat mata, dan oleh karenanya tidak terpikirkan. Out of sight, out of mind.
Kita menyebut hutan hujan tropis di darat sebagai “paru-paru Bumi”, tetapi ternyata organisme kecil yang disebut fitoplankton di lautan melepaskan 70-80 persen oksigen planet ini – jauh lebih banyak daripada pohon. Secara total, lautan menyimpan karbon 50 kali lebih banyak daripada atmosfer kita. Tanpa ini, daerah tropis akan sangat panas dan daerah beriklim sedang akan sangat dingin. Keseimbangan ekosistem membantu menjadikan Bumi sebagai planet yang sempurna bagi kehidupan untuk lahir, tumbuh dan berkembang biak dengan baik.
Sayangnya, cara kerja ekonomi biru (secara sederhana berarti ekonomi berbasiskan sumberdaya laut) saat ini mendorong kerusakan lingkungan yang semakin luas. Masalah polusi plastik yang menjadi kepedulian global warga dunia sesungguhnya hanyalah sebagian kecil dari puncak gunung es yang muncul ke permukaan. Di bawah permukaan, lautan sudah lama sepi dari hidupanliar (wildlife) bawah laut dan kini diisi dengan beberapa spesies ikan budidaya. Zona mati di laut muncul dan meluas saat terjadi proses asidifikasi /pengasaman dan pemanasan suhu laut yang semakin memburuk. Banyak orang tidak mengetahui fenomena ini dan sejauh mana pengaruhnya bagi kehidupan manusia karena kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata.
Armstrong mengajak kita melihat dinamika hubungan manusia yang berubah dengan lautan, dimulai dengan bagaimana sumber daya laut dan perikanan turut memperkaya para pelaut, pemburu paus, dan penjelajah awal. “Eksploitasi dan kerusakan di laut mungkin sama tuanya dengan tradisi berlayar itu sendiri,” tulisnya.
Selama abad ke-17 hingga saat ini, banyak orang percaya bahwa sumberdaya laut tidak akan ada habisnya. Tetapi perspektif ini mulai berubah ketika para pemburu paus harus pindah ke perairan berburu yang lebih berbahaya di daerah kutub karena tangkapan menjadi semakin langka. Pada pertengahan abad ke-20, banyak spesies paus berada di ambang kepunahan.
Namun, hal yang menarik tentang restorasi laut adalah ekosistem laut dapat pulih lebih cepat daripada ekosistem darat. Kehidupan laut terbukti bisa pulih secara signifikan dalam satu generasi manusia. Contohnya, populasi paus mulai meningkat menyusul penurunan perburuan paus komersial, dan keberhasilan ini perlu direplikasi secara menyeluruh, tidak hanya untuk kepentingan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati laut, namun juga untuk keberlanjutan hidup manusia yang bergantung pada laut.
Kita telah mengetahui berbagai jasa laut bagi manusia, dari urusan mengatur iklim, menyediakan sumber pangan, hingga menghasilkan setidaknya separuh oksigen dunia. Dan bagaimana cara kita membalas jasa baik ini? Alih-alih berterima kasih dan melindungi ekosistem laut yang rentan, manusia gemar menghabiskan sumber daya laut yang terbatas secara berlebihan dan mencemarinya dengan tumpahan minyak, sampah plastik, dan kebisingan dari berbagai kegiatan eksplorasi lautan yang sangat mengganggu mamalia laut.
Armstrong, ahli teori politik di University of Southampton, Inggris, mengatakan bahwa jika kita ingin menyelamatkan laut, maka kita harus berubah. Dalam A Blue New Deal, dia berpendapat bahwa institusi dan hukum yang mengatur lautan kita terlalu terfragmentasi, terlalu lemah dan terlalu kalah dengan kepentingan pribadi/golongan tertentu. Institusi dan hukum yang ada juga gagal mengatasi ketidaksetaraan antara negara kaya dan miskin, katanya.
Armstrong mengusulkan pendekatan baru setelah mengajak kita mengurai kekacauan yang kita hadapi. Secara historis, tata kelola laut dibentuk oleh dua gagasan yang berlawanan: kebebasan laut lepas, yang dianut pada tahun 1609 oleh filsuf Belanda Hugo Grotius dalam bukunya The Free Sea; dan gagasan yang lebih umum tentang “enclosure”, yang dengannya negara pantai berhak atas kontrol dan pemanfaatan eksklusif atas lingkungan laut yang berada langsung di wilayahnya.
Visi Grotius tentang lautan yang “bebas untuk semua” akan memungkinkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya laut untuk melakukannya sebanyak dan sesering yang mereka inginkan – karena mereka memiliki sumber daya modal dan sumber daya manusia serta teknologi.
Namun, jelas, pengaturan itu tidak bisa diterapkan lagi mengingat hanya segelintir negara kaya yang mampu membeli teknologi mahal yang dibutuhkan untuk penambangan dasar laut dan ekstraksi mineral seperti dalam biodiversity beyond national jurisdiction/BBNJ.
Argumen menentang ‘enclosure’ mungkin paling baik dijelaskan dengan mengacu pada artikel tahun 1968 oleh ahli ekologi Garrett Hardin, di mana dia mengatakan bahwa “Kebebasan dalam milik bersama membawa kehancuran bagi semua”, biasanya dinyatakan sebagai “tragedi milik bersama” (tragedy of the commons).
Masalah dalam menerapkan prinsip ini di laut, seperti yang ditunjukkan Armstrong, adalah bahwa hal itu belum tentu benar. Catatan sejarah penuh dengan contoh sumber daya yang dimiliki bersama dan diatur secara adil selama ratusan tahun. Dalam pandangannya, “tragedi sebenarnya bagi individu commoners (orang biasa, rakyat jelata) adalah enclosure itu sendiri, yang membuat mereka terusir dari tanahnya oleh tuan tanah yang kaya raya”.
Armstrong menyatakan bahwa masalah yang sama kini terjadi di lautan, dengan negara-negara kaya menikmati status sang tuan kaya raya. Ini terjadi karena Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1994, yang menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membentang hingga 200 mil laut dari hampir setiap pantai. Aturan tersebut mengecualikan negara-negara yang terkurung daratan, termasuk sembilan dari 12 negara termiskin di dunia, dari pembagian ‘bancakan’. Aturan ini tidak menghalangi negara-negara kaya untuk melisensikan hak untuk mengeksploitasi ZEE negara-negara yang terlalu miskin untuk melakukannya sendiri.
Dan, sementara hukum membolehkan setiap atol, batu, dan sepetak pulau milik negara laut untuk dieksploitasi secara eksklusif, nyatanya banyak yang berubah menjadi milik bekas kekuatan kolonial dan negara kuat lainnya. Akibatnya, AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Australia kini menguasai sumber daya lebih dari 45 juta kilometer persegi lautan.
Apakah mungkin kita memiliki kesepakatan baru? Kita tengok versi perjanjian tahun 1961 yang menetapkan Antartika sebagai tempat perdamaian dan kerja sama internasional – dengan kata lain, milik bersama. Tak lama setelah itu, Perjanjian Luar Angkasa PBB tahun 1967 pun mengatur hal yang sama. Bukan mustahil dan di luar kapasitas hukum kita, kata Armstrong, untuk mengatur lautan kita berdasarkan prinsip pengelolaan bersama, prinsip pembagian keuntungan yang lebih adil, dan bahkan untuk transfer teknologi antara negara kaya dan miskin.
Hal yang mungkin Armstrong kurang perhatikan adalah gagasannya yang masih sumir terkait penegakan aturan. Terasa sangat ideal untuk memimpikan sebuah “World Ocean Authority” (Badan Otoritas Lautan Dunia) yang pertimbangannya tidak bisa dimonopoli oleh negara mana pun, baik untuk memveto atau lainnya. Tapi kita belum tahu siapa dan bagaimana kekuatan super itu bisa mengatur dan mendorong agar semua negara dapat berbagi sumber daya laut secara adil dan beradab, dengan mengesampingkan kepentingan pribadi masing-masing dan bergerak semata demi kepentingan bersama.
Armstrong juga merekomendasikan perlindungan 80% lautan sebagai kawasan cadangan laut, yang akan memungkinkan proses regenerasi berlangsung cepat. Prioritas lainnya termasuk mempromosikan budidaya rumput laut, penanaman mangrove, ‘penghijauan’ pelabuhan dan dekarbonasasi kapal-kapal. Kita juga perlu melarang subsidi penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan serta praktik penangkapan ikan yang berbahaya dan merusak seperti penggunaan sianida dan dinamit, serta menciptakan perlindungan hukum yang lebih baik untuk berbagai spesies primata laut seperti paus dan lumba-lumba.
Buku ini menyajikan manifesto radikal untuk menangani dwi krisis di laut, yaitu ketidaksetaraan dan kerusakan lingkungan. Inilah konsep yang Armstrong usung sebagai “A Blue New Deal”.
Disajikan dengan gaya pengisahan yang sangat menarik, buku ini terdiri dari sepuluh bab, dengan Introduction dan Afterword sebelum dan sesudahnya. Kesepuluh bab buku ini disarikan secara singkat sebagai berikut:
Kesimpulannya, buku ini memberikan panduan persuasif untuk pemulihan planet, dan merupakan bacaan yang menginspirasi dan menyegarkan. Penulis sepakat, perlu lebih banyak warna biru di tengah semua pembicaraan tentang pemulihan hijau yang lebih dulu menjadi arus utama. Terlebih karena Bumi mayoritas terdiri dari lautan biru. Karena, ketika lautan rusak maka seluruh planet akan terdampak.
Banyak pujian dilayangkan kepada penulis buku ini, dari mulai Financial Times, National Geographic, The Guardian, The Independent, hingga New Scientist. Intinya, A Blue New Deal sangat direkomendasikan.
Recent Posts
- Hari Laut Sedunia Pentingnya Memitigasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Masyarakat Pesisir Indonesia
- Deteksi dan Analisis Dugaan Praktik Penangkapan Ikan secara Ilegal di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia
- Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) Officer
- Penangkapan Kapal Run Zeng 03 dan Kejahatan Lintas Batas Negara Terorganisir dalam Sektor Perikanan Tangkap
- Historic New Coalition of Unions and Civil Society Organizations
